GEDONG Kirtya adalah sebuah perpustakaan–museum naskah lontar yang unik dan bersejarah di kota Singaraja, Bali.
Didirikan sejak 1928, Gedong Kirtya menyimpan ribuan lontar yang berisi teks-teks sastra, filsafat, sejarah, wariga, pengobatan, pertanian, dan berbagai pengetahuan turun-temurun yang menjadi khazanah budaya tak ternilai.
Gedong Kirtya bahkan didaftarkan sebagai situs cagar budaya setempat sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan atas nilainya sebagai warisan intelektual dan budaya Bali.
Pada saat yang sama, sastra—dalam pengertian yang luas—tidak pernah berhenti menjadi medium yang hidup. Ia bukan sekadar teks di lembaran lontar; ia adalah denyut yang terus mengalir ke dalam praktik kehidupan kontemporer.
Di sinilah Festival Sastra di Singaraja yang didukung Kementerian Kebudayaan RI melalui Dana Indonesiana mengambil peran strategis untuk menjembatani warisan masa lalu dan kehidupan orang banyak saat ini.
Festival ini adalah sebuah perhelatan seni dan budaya yang digagas untuk memaknai kembali gedung-gedung warisan, teks-teks lontar, dan narasi masa lalu melalui praktik sastra kontemporer dan interdisipliner. Festival ini telah diselenggarakan secara berkala sejak Juli 2025 dan menjadi ruang kolaboratif antara penulis, budayawan, akademisi, seniman, pelajar, dan masyarakat luas.

Selama bertahun-tahun, keberadaan Gedong Kirtya lebih banyak dipahami sebagai reservoir pengetahuan yang statis—sebuah museum sunyi yang hanya dikunjungi oleh peneliti dan segelintir pegiat budaya. Namun, melalui festival, Gedong Kirtya diposisikan kembali sebagai ruang hidup dan berdialog yang aktif.
Dalam festival tersebut, Gedong Kirtya tidak hanya menjadi latar atau tempat pameran saja, tetapi dirancang sebagai episentrum aktivasi budaya. Tema dan program festival kerap bersumber dari naskah-naskah lontar yang tersimpan di Gedong Kirtya, seperti Buda Kecapi yang menjadi inspirasi riset sastra tahun 2025—teks usadha kuno yang dijadikan dasar diskusi, pertunjukan teater, pementasan musik, maupun film dokumenter.
Festival ini bukan hanya menampilkan lontar sebagai artefak statis tetapi mendorong alih wahana dari teks ke medium baru yang relevan bagi generasi masa kini.
Alih wahana ini menjadi inti bagaimana sastra mengaktivasi situs cagar budaya tersebut.
Naskah lontar yang semula terbatas hanya dipahami oleh sedikit peneliti kini dialihwahanakan ke dalam bentuk panggung, diskusi publik, workshop, musikalisasi puisi, atau film pendek. Proses ini merevitalisasi warisan budaya sehingga menjadi pengalaman yang dinamis dan bisa dijangkau oleh masyarakat luas—termasuk generasi muda yang mungkin tak akrab dengan lontar sebagai media bacaan klasik.
Sastra, menurut Kadek Sonia Piscayanti, penggerak Festival di Singaraja menjadi bentuk penyembuhan sosial dan personal atas luka identitas yang dialami masyarakat saat ini.
Dalam jumpa persnya, Sonia menjelaskan bahwa melalui alih wahana teks lontar ke berbagai bentuk seni kontemporer—teater, film, musikalisasi puisi, dan karya sastra modern—festival berupaya “menghidupkan masa lalu dalam bentuk yang relevan dan bisa diterima generasi hari ini.”
“Kami merancang festival ini sebagai proses alih wahana dari teks lontar menjadi pertunjukan, karya sastra modern, bahkan film. Jadi kami tidak sekadar mengarsipkan masa lalu, tapi menghidupkannya dalam bentuk yang relevan dan bisa diterima generasi hari ini,” ujar Sonia.
Lebih jauh lagi, festival ini memicu rasa bangga lokal atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Buleleng dan Bali Utara. Dengan menempatkan Gedong Kirtya sebagai pusat inspirasi dan diskusi, SLF membantu menumbuhkan apresiasi baru terhadap lontar sebagai sumber karya sastra, bukan sekadar objek museum.
Hal ini terlihat dari banyaknya program yang berusaha mensosialisasikan pemahaman tentang lontar melalui lomba baca puisi, workshop penulisan, diskusi tentang kontribusi Gedong Kirtya dalam sejarah budaya, hingga dialog antara tradisi lisan dan praktik seni kontemporer.
“Kami bukan hanya ingin membuat peristiwa festival yang sekadar ada. Tapi ini menjadi proses dokumentasi, pemaknaan ulang, dan penciptaan gagasan baru. Karena itu, banyak program kami yang juga bersifat riset dan interpretasi,” ungkap Sonia.
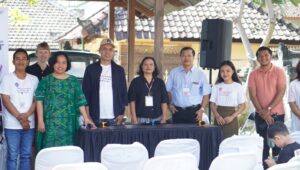
Menurutnya, festival ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap pelupaan, terhadap sentralisasi pengetahuan, terhadap komersialisasi warisan budaya. SLF menjadi semacam panggung untuk suara-suara yang selama ini tidak terdengar atau sengaja dilupakan.
Oleh karena itu, sastra berperan sebagai penggerak utama aktivasi budaya di Gedong Kirtya: ia memberi kesempatan bagi warisan sejarah yang tersimpan dalam lontar untuk dibaca, direnungkan, dan diinterpretasikan ulang dalam konteks sosial budaya masa kini.
Sastra bukan hanya retorika atau estetika: ia menjadi medium hidup yang menjembatani masa lalu dan masa depan, serta memperkuat relevansi cagar budaya dalam kehidupan publik.
Dengan cara ini, cagar budaya Gedong Kirtya tumbuh dan bertransformasi menjadi ruang narasi kolektif, tempat di mana nilai-nilai budaya, pengetahuan lokal, dan kreativitas bertemu untuk dirayakan bersama. (bs)

