Oleh Lewa Karma **)
KONSEP ekoteologi menurut para ahli adalah disiplin yang menggabungkan ilmu teologi dan ekologi untuk memahami hubungan antara agama dan lingkungan, serta menggunakan nilai-nilai agama untuk mengatasi krisis lingkungan.
Berangkat dari tesis Seyyed Hossein Nasr (2012) yang mengatakan bahwa sainstisme modern adalah akar dari krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Ia menawarkan solusi melalui pergeseran paradigma (paradigm shift) dari saintisme modern menuju pandangan yang secara khusus berbicara tentang realitas kosmis secara mendasar, yaitu kosmologi.
Kosmologi yang ditawarkan oleh Nasr sebagai paradigma sains adalah kosmologi tradisional, yaitu filsafat alam yang berakar dari ajaran-ajaran tradisional yang mengaplikasikan prinsip-prinsip metafisika dalam ranah jagat raya.
Nasr juga menekankan bahwa Al-Qur’an dan hadist mengajarkan manusia untuk memandang alam sebagai amanat Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Pandangan ini menekankan kesadaran bahwa alam adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, sehingga sikap eksploitatif harus dihindari.
Demikian juga Nasarudin Umar (Menteri Agama RI; 2024) mengaitkan ekoteologi dengan tafsir Asma’ul Husna yang menekankan sifat-sifat feminin Tuhan ( Rahman dan Rahim) dan menolak teologi maskulin yang antroposentris.
Ia memandang menjaga lingkungan sebagai ibadah, dengan tiga prinsip utama: kasih sebagai dasar hubungan manusia-alam, menolak teologi maskulin demi teologi feminin, dan melihat penjagaan lingkungan sebagai ibadah konkret.
Lebih lanjut, dari pandangan ini juga diambil irisan antara konsep ekoteologi Islam dengan Filosofi Tri Hita Karana yang ada dalam pandangan masyarakat Bali.
Jamak diketahui bahwa Tri Hita Karana merupakan konsep hidup masyarakat Bali yang memadupadankan nilai ketuhanan, kemanusiaan dan semesta dalam menjaga entitas ekologi dan teologi secara bersamaan.
Pada dasarnya, ekoteologi Islam dan Tri Hita Karana menawarkan landasan moral yang kuat untuk mengatasi krisis ekologis saat ini. Keduanya sepakat bahwa pemisahan antara aspek spiritual, sosial, dan alamiah kehidupan adalah akar masalah kerusakan lingkungan.
Dalam bukunya Thomas Berry (2006) yang berjudul “Evening Thoughts: Reflecting on Earth as Sacred Community”, menyatakan bahwa kehancuran bumi dan segala makhluk yang hidup di dalamnya. Tesisnya menekankan pentingnya penataan ulang hubungan manusia dengan alam yang didasarkan pada pemahaman tentang evolusi alam semesta.
Menurut Berry, proses evolusi alam semesta sejak awal mengandung aspek psikis-spiritual dan material-fisikal yang tidak dapat dipisahkan, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan merawatnya. Setiap komponen geologis, biologis, dan manusia sebagai bagian dari komunitas bumi, saling terikat dan hadir untuk mendukung satu sama lain.
Berikutnya, ekoteologi Islam didasarkan pada dua konsep sentral, yaitu : Kesatu, Khalifah (Mandat Kepemimpinan). Manusia dipandang sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi, bukan sebagai pemilik tunggal atau penguasa mutlak. Mandat ini menuntut tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan melestarikan bumi dengan adil dan bijaksana, bukan merusaknya (fasad).
Kedua, Mizan (Keseimbangan). Al-Qur’an menekankan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang (mizan). Tugas manusia adalah menjaga keseimbangan ini. Merusak lingkungan berarti mengganggu mizan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.
Ajaran Islam memandang alam sebagai “ayat-ayat” (tanda-tanda) kekuasaan dan keagungan Allah yang harus direnungkan dan dihormati. Sementara konservasi terhadap lingkungan adalah bagian dari ketaatan (taqwa) dan ibadah.
Sementara itu, masyarakat Bali dalam peradabannya juga memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradaban sejak jaman dikenalnya kebudayaan yang terkenal dengan konsep kosmologi Tri Hita Karana dan merupakan falsafah hidup yang bertahan hingga kini walaupun berada dalam konsep-konsep perubahan sosial yang selalu berdinamika sebagai salah satu ciri atau karakter peradaban.
Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menurut Wiana ( 2004 : 141) menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Tri Hita Karana menyediakan struktur praktis untuk hidup harmonis melalui tiga pilar, yaitu : Pertama, Parhyangan merupakan hubungan harmonis dengan Tuhan. Kedua, Pawongan, merupakan hubungan harmonis dengan sesama manusia. Ketiga, Palemahan, merupakan hubungan harmonis dengan alam/lingkungan.
Menurut Bakti (2012) bahwa setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati (jagadhita) hanya dapat dicapai jika ketiga hubungan ini seimbang dan terawat. Alam (Palemahan) memiliki posisi sakral karena merupakan anugerah dan manifestasi dari Yang Ilahi (Hyang Widhi).
Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang dari pada segala tindakan berekses buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai.
Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak oleh tangan-tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan memusuhinya. Jangan salahkan bilamana terjadi musibah, kalau ulah manusia suka merusak alam lingkungan.
Irisan antara ekoteologi Islam dan Tri Hita Karana terletak pada penegasan bahwa tindakan ekologis berakar pada keyakinan teologis dan etika komunal.
Pertama, Basis Teosentris adalah kerangka yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari eksistensi. Baik konsep “Khalifah” (Mandat Kepemimpinan) dalam Islam maupun “Parhyangan” dalam Tri Hita Karana menegaskan bahwa penghormatan terhadap alam adalah turunan langsung dari penghormatan terhadap Sang Pencipta. Tidak ada dikotomi antara spiritualitas dan materialitas lingkungan.
Kedua, Etika Tanggung Jawab (Awig-awig dan Fiqih Lingkungan) menempatkan ekoteologi Islam yang mengembangkan Fiqih Lingkungan (hukum Islam tentang lingkungan) yang menyusun aturan berbasis syariah untuk konservasi.
Ini selaras dengan awig-awig (hukum adat) di Bali, dimana sanksi adat dikenakan bagi perusak lingkungan. Kedua sistem ini menggunakan otoritas moral dan komunal untuk memastikan keberlanjutan.
Ketiga, Keseimbangan (Mizan) dan Harmoni. Mizan dalam Islam sangat paralel dengan prinsip harmoni dalam Tri Hita Karana. Keduanya menekankan pentingnya hidup dalam batas-batas ekologis yang wajar dan menolak eksploitasi berlebihan.
Berikutnya, implikasi konsep ekoteologi dalam irisan Islam dan Tri Hita Karana menjawab tantangan zaman dan etik. Hal ini diharapkan bisa membawa dampak positif dalam menjaga ajegnya ekologis melalui irisan konsep ekoteologi. 1. Mengubah paradigma, bahwa ekoteologi bertujuan untuk mengubah cara pandang (paradigma) manusia terhadap alam dari objek konsumtif menjadi subjek yang memiliki hak dan nilai intrinsik. 2. Menjembatani agama dan sains, menjembatani pemahaman ilmiah tentang dunia (kosmologi, biologi, ekologi) dengan konsep teologis tradisional. 3, Mendorong ibadah konkret, menjadikan tindakan menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah yang nyata dan tidak hanya refleksi teologis. 4. Menumbuhkan kesadaran:, menggunakan otoritas dan perangkat keagamaan untuk menghadapi paradigma konsumerisme dan prilaku eksploitatif, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.
Menggabungkan perspektif ekoteologi Islam dengan Tri Hita Karana menghasilkan sinergi yang kuat. Ekoteologi Islam menyediakan landasan universal berdasarkan wahyu, sementara Tri Hita Karana menyediakan model implementasi lokal yang terbukti efektif dalam menjaga bentang alam dan budaya Bali.
Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis iklim bukanlah sekadar masalah teknis atau ekonomi, melainkan masalah etika dan spiritual yang mendalam. Mereka mengajak umat manusia, terlepas dari latar belakang agama spesifik, untuk kembali ke fitrahnya sebagai bagian integral dari alam yang bertugas sebagai pemelihara yang bertanggung jawab. []
Keterangan :
*) : Opini dalam rangka sharing gagasan Mata Kuliah Etnosains pada Institut Mpu Kuturan (IMK) Singaraja
**) : 1) Ketua PC Pergunu Buleleng; 2) Kasi Pendis Kemenag Buleleng; 3) Mahasiswa Program Doktoral Prodi Ilmu Agama & Kebudayaan IMK
Daftar Pustaka
1. Al-Hafizh, M. R. (2011). Ekoteologi Islam: Prinsip dan Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
2. Bakti, I. Made. (2012). Tri Hita Karana: Perspektif Hindu Bali dalam Memandang Lingkungan. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 8 (1), 1-10.
3. Berry, Thomas. The Sacred Universe: Earth, Spirituality, and Religion in the Twenty-First Century, New York: Columbia University Press, 2009.
4. ____________. Evening Thoughts: Reflecting on Earth as Sacred Community. San Fransisco: Sierra Club Books, 2006
5. Fahruddin, A. (2015). Ekoteologi dalam Perspektif Islam: Menyelamatkan Lingkungan dengan Spiritualitas. Jurnal Analisa, 22(2), 209-224.
6. Nasr, Seyyed Hossein. Islam in The Modern World: Challenged by the West, Threatened by Fundamentalism, keeping Faith with Tradition. New York: HarperOne, 2012. Palmer, C. (2008). Environmental Ethics: An Introduction. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
7. Wirartha, I Made. (2006). Filsafat Tri Hita Karana. Denpasar: Yayasan Dhana Saraswati.

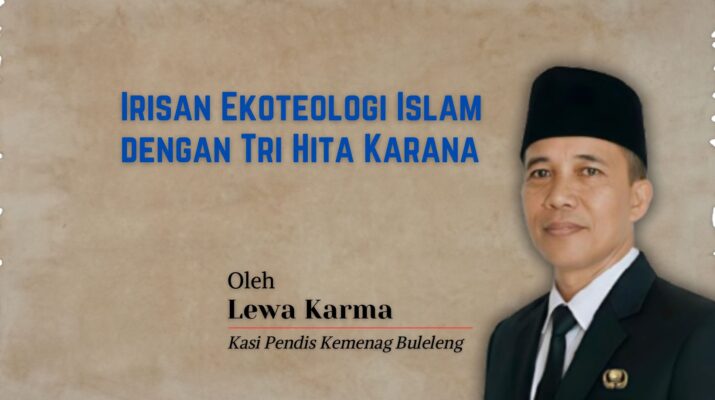
Belajar menulis untuk mengikatkan diri pada ilmu pengetahuan, mohon saran dan masukannya